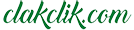Oleh: Hariadi Kartodihardjo | Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB
Membuat keputusan dilakukan siapa saja. Dari hal-hal kecil atas kehidupan sehari-hari, hingga hal-hal besar dan krusial, seperti para pendiri bangsa ini ketika memutuskan membacakan Proklamasi
Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proses menentukan keputusan pun sangat beragam. Dari hanya sekadar merenung, menggalang pendapat, dan di zaman Internet ini memakai big data.
Perhatian saya dalam pengambilan keputusan bukan pada skala besar-kecil atau tingkat kesulitan mencari informasi penunjangnya, tapi pada kemandirian atau kemerdekaan dalam prosesnya. Para kolega di pemerintahan, lembaga legislatif, konsultan, lembaga donor, atau perusahaan swasta pernah mengalami tekanan-tekanan ketika mengambil sebuah keputusan. Mereka bisa tidak merdeka, dalam arti menjalankan kebebasan sesuai mandatnya.
Apabila proses kemerdekaan Indonesia 75 tahun lalu diasosiasikan dengan perlawanan “merdeka atau mati”, dengan apa proses pengambilan keputusan menuju kemerdekaan itu harus diasosiasikan?
Dalam kondisi tertekan selalu tersedia jalan pintas yang memungkinkan seseorang membuat keputusan dengan cepat. Disebut juga heuristik, baik heuristik ketersediaan maupun heuristik keterwakilan. Kendra Cherry (2019) dalam The Psychology of Decision-Making Strategies menjelaskan kedua konsep itu berikut ini:
“Heuristik ketersediaan” berjalan ketika kita mencoba menentukan seberapa besar kemungkinan sesuatu terjadi, dengan mengingat peristiwa serupa yang terjadi di masa lalu. Misalnya, jika akibat tekanan Anda harus mengambil keputusan dengan melanggar peraturan, Anda mungkin mengingat beberapa orang yang melakukan hal sama. Bila orang yang jadi referensi itu selamat, Anda akan mengikutinya karena keputusan dengan melanggar aturan ternyata tak berisiko.
Sementara “heuristik keterwakilan” adalah membandingkan situasi kita saat ini dengan “prototipe” kita dari peristiwa atau perilaku tertentu. Misalnya, ketika Anda akan membuat keputusan dengan melanggar hukum dan menganggap diri Anda adalah orang yang kebal hukum, Anda tak akan ragu membuat keputusan yang tak sesuai aturan.
Pendekatan itu menunjukkan kemerdekaan mengambil keputusan bagi seseorang tergantung pada kapasitasnya dalam menentukan posisi dirinya sendiri. Ia mestinya membebaskan diri dari contoh-contoh pelanggaran bernasib baik atau melepaskan diri dari prototipe diri sendiri sebagai tipe setia walau harus melanggar hukum.
Hal lain: seseorang bisa terkesima pada propaganda yang memuliakan nilai-nilai luhur, seperti kebebasan atau patriotisme. Biasanya nilai sakral dipakai mengaburkan apa yang terjadi di baliknya.
Kebebasan untuk semua, dalam kasus tertentu, adalah benar. Kita bisa memakai kebebasan berpikir dan berekspresi tanpa merugikan orang lain. Tapi dalam kasus lain, kebebasan satu orang adalah penjara bagi orang lain.
Ketika toko-toko serba ada dibebaskan masuk ke pelosok-pelosok desa, warung-warung kelontong bangkrut karena kalah bersaing. Ketika orang sangat kaya memiliki tambang dan kebun-kebun ratusan ribu hektare tak membayar pajak, ada orang lain yang menderita karena layanan publik menjadi tersendat.
Dalam RUU Cipta Kerja, misalnya, pemodal akan bebas merancang instrumen perizinan yang longgar. Ketika itu terjadi, kita semua akan membayar krisis yang ditimbulkannya. Para pengusaha menuntut kebebasan dari sesuatu yang mereka sebut “birokrasi”. Padahal birokrasi adalah instrumen negara untuk melindungi publik. Maka ketika peran birokrasi surut untuk membuka keran investasi, sesungguhnya publik tak terlindungi dari dampak buruknya.
George Monbiot dalam The Problem with Freedom di the Guardian, 5 April 2017, menyebut bahwa kebebasan bisa dipakai untuk merobohkan birokrasi sebagai pelindung publik. Perusahaan paling kotor dan paling mengotori lingkungan harus mengeluarkan uang politik lebih banyak agar sistem politik menjadi milik mereka. Politisi konservatif seperti Boris Johnson dan Michael Gove di Inggris memperjuangkan kebebasan perusahaan-perusahaan hitam karena mendapat insentif. Argumen mereka dalam deregulasi serupa dengan semangat RUU Cipta Kerja untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif.
Benar kata Sukarno, proklamator kemerdekaan Indonesia itu: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk situasi sekarang, saya menafsirkan pesan itu lebih berkaitan dengan politik melawan tekanan untuk mewujudkan gagasan-gagasan baru yang mendapat tantangan sangat besar.
Kini, setelah merdeka 75 tahun, pesan dan perintah dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga yang mewakili publik, seringkali membingungkan. Mungkin karena “musuh” itu bukan mereka yang jadi penjajah, tapi bagian dari kita, dari negara yang mengonstruksi regulasi. Kemiskinan, misalnya, adalah desain yang diciptakan. Sebagaimana dinyatakan Nelson Mandela: Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made.
Masyarakat luas hampir tidak berdaya karena melawan “penjajah” di hari ini, yang berarti melawan peraturan, melawan pejabat-pejabat, lalu dianggap melawan negara. Sungguh tidak mudah menghayati bagaimana seseorang atau masyarakat menderita akibat kebijakan yang sah, dibungkam aparat keamanan, seperti masyarakat yang diusir dari lokasi-lokasi tambang, hutan, dan perkebunan skala besar.
Masalahnya, jika kita diam, kita juga akan terus jadi korban. Seperti kata Wiji Thukul, sastrawan, buruh, dan pejuang hak asasi manusia, dalam potongan sajaknya: Jika kau tak lagi berani bertanya. Kita akan jadi korban keputusan-keputusan.
Memerdekakan diri di masa kemerdekaan bukan hanya soal menggali kekuatan dan menghimpun kekuasaan, sebaliknya juga soal membangun kesadaran, kesabaran, keberanian menjalankan sesuatu atas dasar kemanusiaan. Seperti dalam potongan sajak Chairil Anwar ini: Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang...
Keberhasilan proses menuju kemerdekaan mengambil keputusan bukan hanya diukur atas apa yang bisa dicapai, tetapi apa yang sudah ditegakkan untuk bangun kembali. Perang di zaman merdeka menghadapi musuh dengan senjata psikologis. Maka, semangat untuk memenangi perjuangan pada masa kemerdekaan juga harus berani melawan pengabaian, bahkan ancaman kematian, untuk mewujudkan kemenangan yang sesungguhnya.
Mahatma Gandhi pernah mengatakan, “First they ignore you, then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” Pertama mereka akan menolakmu, lalu menertawakanmu, kemudian mereka mengajar kamu. Lalu kamu yang menang. Tentu jika kita melawan.
*Artikel ini sudah dipublikasikan di majalah Forest Digest dalam rubruk Surat dari Darmaga dan dishare di akun facebook Hariadi Kartodihardjo, 10 Agustus 2020