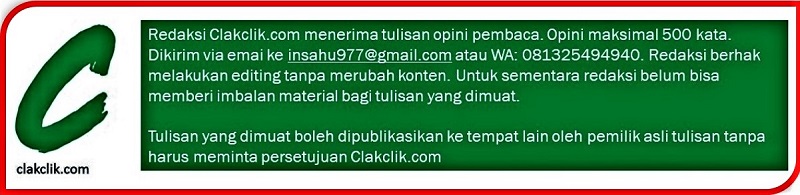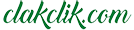Oleh: Husaini | Pengelola Omah Buku ‘Uplik Cilik’ | Tinggal di Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah
Hadirnya unit-unit industri diyakini akan menjadi penggerak pusat pertumbuhan. Sebuah pandangan yang terkesan hampir dianggap 100 persen benar bahwa kehadiran sebuah industri akan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Konsep ini sudah lama diyakini terutama oleh akademisi dan ilmuan plat merah (yang biasa menjadi stempel pemerintah). Konsep itu pertama kali digagas oleh Francois Perroux, ekonom Perancis.
Pusat pertumbuhan, dengan industri sebagai pemantik, diyakini memberikan manfaat bukan hanya bagi daerah sekitar, melainkan juga mengalir ke daerah belakang (hinterland), atau dikenal dengan trickle down effect (tetesan ke bawah) dalam bentuk tumbuhnya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pemasok bahan baku.
Pusat-pusat pertumbuhan berbasis industri memang terbukti (pernah) memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahun 1992, majalah Time mencatat bahwa sumbangan sektor industri pada produk domestik bruto (PDB) di Indonesia mencapai 25 persen dan karena itu negara kita waktu itu sudah digolongkan sebagai ”A New Tiger of Asia” (”Macan Baru Asia”).
Namun demikian, ditengah perjalanan, paham yang sudah dipraktikkan puluhan tahun itu terseok-seok. Hal ini disebabkan karena peran pemasok bahan baku tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hubungan hulu dan hilir (backward-forward linkage) sangat minim.
Hal itu disebabkan karena jenis-jenis industri yang dibangun pada umumnya tidak berkaitan dengan bahan baku yang tersedia di daerah belakang, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Industri-industri yang demikian disebut sebagai footloose atau tidak mempunyai basis dengan ekonomi lokal.
Fenomena ini yang sering dikritik almarhum Prof Mubyarto, tokoh ekonomi kerakyatan, bahwa kehadiran industri tidak memberikan nilai tambahan lokal yang berarti karena tidak berbasis pada ekonomi lokal.
Daerah belakang yang berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan ibarat jatuh tertimpa tangga. Di satu sisi, sumber daya dalam bentuk tenaga kerja dan modal tersedot ke pusat pertumbuhan dan di sisi lain terus terdesak oleh kegiatan industri melalui alih fungsi lahan dan dampak lingkungan.
Sejumlah industri yang saat ini sudah masuk di Kabupaten Pati (Pabrik Garment di Margorejo, Pabrik Sepatu di Batangan, misalnya) tampaknya merupakan industri yang footloose itu. Industri yang bedol deso dari negeri asalnya karena faktor pajak yang mahal, peraturan lingkungan yang makin ketat, dan kejenuhan lokasi industri.
Bentuk relokasi industri seperti itu minim transformasi dengan potensi lokal, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja terampil, maupun alih teknologi.
Menurut catatan Kementerian Riset dan Teknologi/Pendidikan Tinggi (2018), sebanyak 58 persen industri di Indonesia memilih mengambil oper inovasi teknologi dari negara mereka berasal.
Bagi daerah sekitar, kegiatan industri menimbulkan dampak lingkungan berupa pencemaran air, udara, kemacetan, dan kebisingan. Alih fungsi lahan dari tambak dan sawah menjadi industri membawa serta meningkatnya air larian yang berakumulasi menjadi banjir.
Dalam konteks Kabupaten Pati, kita bisa saksikan hal ini di Sungai Juwana. Pada saat musim kemarau, air Sungai Juwana selalu memperlihatkan tanda-tanda tercemar; kadang berubah warna menjadi hitam pekat atau merah dan sesekali berbau.
Di Bulan Juli ini, kita juga menyaksikan bagaimana warga melakukan protes secara virtual atas bau busuk yang menyebar di sejumlah kecamatan yang bersumber dari industri perikanan ditepi Jalan Pantura Pati-Juwana. Protes virtual dilakukan karena mereka sudah jengah, selama hampir 5 tahun masalah bau busuk yang dikeluhkan tak diatasi oleh pemerintah.
Industri yang menjadi mesin pertumbuhan harus menerapkan prinsip produksi bersih yang mengelola lingkungan sejak pemilihan bahan baku, proses produksi, bahan jadi, sampai pada pengiriman.
Semua pihak harus sadar bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan akan memerlukan biaya pemulihan yang mahal.