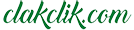Hegemoni kekuasaan akan memanipulasi ilmu pengetahuan dalam menelurkan kebijakan publik yang merusak lingkungan. Otokritik untuk para ilmuwan dan perguruan tinggi.
Oleh: Hariadi Kartodihardjo; Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB
Dalam acara halal bi halal Pusat Studi Lingkungan IPB University, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan pandangan menarik. Menurut dia seharusnya tidak ada manipulasi terhadap ilmu pengetahuan oleh suatu kepentingan.
Dengan kata lain, semestinya tidak ada hegemoni terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang mengancam keilmuan. “Ciri hegemonial itu juga seolah akan membawa urusan lingkungan ke dalam perspektif ilmiah terkait metodologi, definisi, batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi, dan sebagainya,” kata Siti Nurbaya.
Pandangan ini bisa menggugah karena memunculkan serangkaian pertanyaan lain. Misalnya, apakah kita sudah mengambil pandangan kritis tentang apa isi “ilmu pengetahuan”, bagaimana ia dibentuk, apakah ada hegemoni sehingga pengetahuan digunakan apa adanya, seperti metodologi, definisi, ataupun cara berfikir mengenai sesuatu?
Apakah kita sadar ada “politik pengetahuan” yang secara nyata memproduksi dan menggunakan berbagai definisi yang tidak tepat, baik secara konseptual maupun etis? Apakah kita pernah membahas jenis perubahan struktural yang diperlukan oleh suatu perguruan tinggi, setelah mengakui adanya perubahan epistemologis maupun politis dari budaya pengetahuan kontemporer kita?
Saya jadi ingat Hans N. Weiler. Dalam “Whose Knowledge Matters? Development and the Politics of Knowledge” (2010) ia juga mengupas pertanyaan serupa ketika mengurai relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurut dia, pengetahuan melegitimasi kekuasaan, dan sebaliknya, pengetahuan dilegitimasi oleh kekuasaan. Ada banyak bukti hubungan simbiosis keduanya, di mana keputusan politik dibenarkan dengan mengacu pada lembaga pengetahuan tertentu.
Kenyataan seperti itu semestinya membangunkan kesadaran kita. Berbagai kandungan ilmu pengetahuan yang paling relevan secara etis—yaitu yang berpengaruh terhadap upaya menyejahterakan rakyat secara adil—perlu dicermati kembali implikasinya secara positif maupun negatif. Dalam “The political use of knowledge in the policy process”, Falk Daviter (2015) membahas pengamatan implementasi ilmu pengetahuan yang lebih spesifik bahwa di pemerintahan yang kompleks tidak ada keputusan yang baik. Sebaliknya, pembuat kebijakan biasanya memakai ilmu pengetahuan yang mendukung kontrol politik.
Daviter menyebut pemakaian ilmu pengetahuan yang diharapkan adalah ilmu yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mewujudkan keadilan. Fakta menujukkan kebijakan berada dalam ikatan kelembagaan dan struktur pengambilan keputusan yang secara administratif berjalan dengan kepentingannya sendiri.
Dalam hubungan timbal balik antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan, bisa muncul hegemoni oleh satu kelompok untuk memberi pengaruh yang tidak semestinya kepada masyarakat luas. Dalam teori hubungan internasional, hegemoni sebuah negara membuatnya bisa mengontrol akses bahan baku, sumber daya alam, modal dan pasar, ataupun menghasilkan ideologi yang dapat menyediakan barang publik tertentu seperti keamanan atau stabilitas komersial dan keuangan (Luis, 2018).
Dalam Marxisme, Antonio Gramsci menyebutkan bahwa kelas penguasa bisa memanipulasi sistem nilai dan adat istiadat masyarakat. Berbeda dengan pemerintahan otoriter, dalam hegemoni justru mereka yang terkena dampaknya juga menyetujui dan ikut memperjuangkan tujuan hegemoni sehingga menjadi bagian dari akal sehat dan logika orang banyak (Timothy, 2015).
Shiva (1988) dalam “Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity”, yang disunting oleh Ashis Nandy, menyatakan bahwa sains modern yang bersifat reduksionis cenderung mendukung struktur ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi, maksimalisasi laba, dan akumulasi modal. Pada titik itu sains menjadi akar krisis ekologi.
Penggunaan sains reduksionis modern menjadikan “metode ilmiah” sebagai satu-satunya cara obyektif, netral, dan universal dalam menemukan fakta-fakta alam dan memahami alam dengan benar. Hal ini yang dimaksud Menteri Lingkungan bahwa perspektif ilmiah terkait metodologi dan definisi hutan terpengaruh oleh sebuah kepentingan.
Pandangan yang cenderung menyeragamkan itu bisa ditolak. Semua ilmu pengetahuan dibangun melalui variasi sejumlah metodologi. Tidak ada prosedur tunggal atau seperangkat aturan yang menjamin bahwa suatu penelitian itu “ilmiah” sehingga bisa dipercaya. Para ilmuwan selalu merevisi standar, prosedur, dan kriteria rasionalitas mereka ketika mereka bergerak bersama dan mungkin sepenuhnya mengganti teori dan instrumen saat mereka memasuki domain penelitian baru.
Sementara itu, pandangan pengetahuan ilmiah sebagai deskripsi faktual murni tentang alam juga secara ekologis tidak berdasar (Shiva, 1988). Ekologi mempersepsikan hubungan antara elemen-elemen berbeda dalam suatu ekosistem. Sifat-sifat elemen atau sumber daya tertentu yang dipilih untuk diteliti tergantung pada prioritas dan nilai-nilai peneliti yang memandu persepsi terhadap alam itu.
Maka, tidak ada fakta netral tentang alam yang tidak tergantung pada nilai-nilai yang dibentuk oleh kognisi manusia atau peneliti maupun aktivitas suatu perekonomian. Oleh karenanya, persepsi terhadap alam bergantung pada bagaimana seseorang melihatnya dan bagaimana kepentingannya.
Dengan begitu, nilai-nilai ekonomi akan menghasilkan persepsi dan penggunaan alam yang dapat memperkuat nilai-nilai tersebut. Nilai maksimalisasi keuntungan, misalnya, menentukan cara tertentu dalam memandang alam. Dasar pemikiran mengenai maksimasi keuntungan itu secara agregat nasional digunakan sebagai ukuran efisiensi ekonomi. Dalam praktiknya juga menghasilkan biaya sosial dan ekologis yang ditanggung orang banyak. Michael Porter menyebutnya biaya eksternalitas.
Di Indonesia, keterkaitan antara sains modern dan sistem ekonomi berbasis laba bisa dilihat dalam berbagai masalah berkepanjangan konflik lahan, perusakan kawasan-kawasan lindung, pelanggaran tata ruang ataupun kriminalisasi petani. Berbagai mode pengetahuan alternatif yang bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah itu, yang lebih berorientasi pada manfaat sosial daripada keuntungan pribadi atau perusahaan, belum bisa menempatkan pemikiran atau ilmu pengetahuan sebagai basis utamanya.
Dalam kondisi seperti itu, kesadaran atas berkerjanya politik pengetahuan secara umum belum begitu tinggi. Sebagian akademisi menikmati kategori ahli bahkan mungkin menikmati status kesenjangannya dengan non-ahli. Padahal, kesenjangan mengubah itu mendorong mereka yang awam makin menjadi buta akan sebuah informasi. Klaim sains modern bahwa manusia menjadi penerima manfaat pengetahuan ilmiah, dalam kenyataannya orang miskin dan awam menjadi korban terburuknya.
Dalam bidang kehutanan ada doktrin “scientific forestry”. Doktrin ini sudah banyak dikritik. Peter Gluck (1987) mengurai doktrin ilmu kehutanan berupa “kayu sebagai unsur utama (timber primacy)”, “kelestarian hasil (sustained yield)”, “jangka panjang (the long term)” dan “standar mutlak (absolute standard)”. Doktrin yang berasal dari Eropa itu berkembang di Amerika Utara dan menyebar ke seluruh dunia. Keempat doktrin itu telah membentuk kerangka dasar kurikulum bagi pendidikan tinggi kehutanan serta menjadi isi peraturan di banyak negara.
Jack C. Westoby (1913–1988), Kepala Divisi Kehutanan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam ceramahnya di Universitas California pada 1985 mengingatkan bahwa para ilmuwan perlu lebih rendah hati memeriksa hipotesis mereka sendiri secara mendalam. Pada Kongres Kehutanan Sedunia di Meksiko di tahun yang sama, ia juga mengatakan bahwa “Tugas pertama rimbawan bukan untuk majikan mereka, tetapi untuk kepentingan publik”. Jauh sebelum itu pada 1967, ia mengatakan sebuah kalimat yang terkenal, “Kehutanan bukan tentang pohon, tetapi tentang manusia. Dan bila tentang pohon hanya sejauh pohon dapat melayani kebutuhan masyarakat”.
Dengan kenyataan-kenyataan seperti itu, lembaga-lembaga pendidikan tinggi perlu mengevaluasi secara kognitif rasionalitas dan kemanjuran sistem pengetahuan reduksionis dan non-reduksionis. Hegemoni maupun sains reduksionis mungkin mendapat dukungan politik, kekuasaan negara, ataupun kekuasaan supra struktur. Untuk itu perlu evaluasi secara independen dengan keterbukaan pemikiran dengan memperhatikan berbagai kenyataan penerapan ilmu pengetahuan di lapangan.
Pada 2017, Henry Giroux (2017), guru besar McMaster University Kanada, dalam “Why universities must defend democracy” mengingatkan bahwa universitas harus mendefinisikan diri mereka sebagai barang publik, ruang perlindungan untuk mempromosikan cita-cita demokrasi, imajinasi sosial, nilai-nilai sipil dan kewarganegaraan yang terlibat secara kritis.
Giroux mengutip Jon Nixon, ahli pendidikan, yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi harus dikembangkan sebagai ruang terlindung untuk berpikir walau bertentangan dengan pendapat umum, ruang mempertanyakan kebijakan publik, membayangkan dunia dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, merefleksikan diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain dan, dengan demikian, memahami apa artinya memikul tanggung jawab.
*) Pertama kali diterbitkan di Majalah Forest Digest dalam rubrik Surat dari Darmaga, 22 Juni 2020. Clackclik.com mendapatkan ijin dari penulis untuk mempublikasikan semua tulisan yang diposting di akun Facebook penulis.