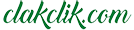Tempe, makanan asli Indonesia, telah mendunia, dan pemerintah akan mendaftarkan tempe sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Namun, di tengah upaya tersebut, tempe di Indonesia justru dihasilkan dari kedelai impor.
Oleh: Fadly Rahman | Dosen Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Padjadjaran
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendaftarkan tempe sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Niat mulia ini bukan yang pertama kali dilakukan. Tahun-tahun sebelumnya—terlebih setelah tempe ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada 2017—langkah pengajuannya ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) ini pernah pula dilakukan seperti oleh Pergizi Pangan dan Forum Tempe Indonesia.
Upaya itu tentu sejalan dengan promosi Gastronomi Nusantara yang sekarang ini diprogramkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Jika melihat citra masa lalu tempe, sepertinya tidak terbayangkan bagaimana bisa makanan berbahan baku kacang kedelai kegemaran rakyat ini bisa mendunia dan bahkan hendak dipatenkan sebagai warisan dunia milik Indonesia (biasanya ini untuk mengantisipasi agar produk-produk budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain).
Impian untuk memopulerkan tempe lebih besar lagi pernah dicetuskan mendiang Onghokham. Dalam antologi 1000 Tahun Nusantara (2000) yang diterbitkan Kompas dalam rangka menyambut milenium baru, sejarawan ini menulis artikel Tempe: Sumbangan Jawa untuk Dunia. Dalam penutup tulisannya, ia mengatakan, ”Jadi, untuk memopulerkan tempe lebih besar lagi, tidak hanya perlu pertimbangan selera dan kecocokan budaya, tetapi juga ketersediaan bahan bakunya.... Oleh karena itu, perlu swasembada kacang kedelai, lebih daripada beras.”
Sebagai sejarawan, pernyataan Onghokham sangat beralasan jika melihat fakta historis perihal hubungan tempe dengan ketersediaan kedelai (Glycine max). Kedelai sedianya dijadikan sebagai bahan makanan pokok yang cocok untuk mengimbangi tingginya konsumsi beras di kalangan rakyat Indonesia. Apalagi pembudidayaannya telah mengakar dalam jejak pangan Indonesia sejak masa kuno. Dari hasil penelitian arkeologis yang dilakukan Antoinette M Barrett Jones (1984), pembudidayaan kedelai kemungkinan sudah dimulai di Jawa sejak masa sebelum abad ke-10 M.
Dari abad ke abad, pemanfaatan kedelai sebagai bahan konsumsi massa makin meluas di Jawa. Dari catatan para peneliti Eropa sejak abad ke-17 oleh Rumphius hingga awal abad ke-20 oleh FW Donath, di samping beras, produksi kedelai di Jawa begitu melimpah. Surplus kedelai ini mendorong kreativitas orang-orang di Jawa Tengah yang diduga sejak abad ke-17 telah menemukan teknik peragian kulit kedelai yang masak dengan memanfaatkan Aspergillus oryzae, sejenis jamur yang tumbuh di iklim tropis Nusantara (faktor alamiah ini menjadi fakta paling dasar yang digunakan untuk memperkuat bukti bahwa tempe diciptakan pertama kali di Indonesia).
Pada abad ke-19, pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dan Undang-Undang Agraria. Kebijakan ini membuka banyak lahan perkebunan (tembakau, teh, dan kopi) di Jawa. Konsekuensinya, aktivitas para petani untuk bertani dan beternak menjadi berkurang ketika mereka dipekerjakan secara paksa di perkebunan-perkebunan kolonial.
Kondisi ini membuat terbengkalai lahan-lahan pertanian dan peternakan karena tidak tergarap oleh para petani. Kualitas gizi mereka dan keluarganya menurun. Untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan sumber protein yang murah untuk mencukupi kebutuhan gizinya.
Jelang akhir abad ke-19, penyelidikan gizi di Hindia Belanda mulai berkembang sebagai respons para ilmuwan terhadap kondisi memprihatinkan kesejahteraan hidup di negeri jajahan. M Greshoff, seorang botanis, pada 1890 menulis artikel bertajuk ”De Soja boon en hare betekeenis als voedingsmiddel voor Nederlandsch Indië” (kacang kedelai dan manfaatnya sebagai bahan makanan di Hindia Belanda). Ia melaporkan sebuah kongres kesehatan di Paris pada 1889 yang menampilkan demonstrasi memanggang roti dan biskuit dengan menggunakan tepung kacang kedelai sebagai bahan bakunya.
Seorang dokter bernama Stokvis menyimpulkan produk roti dan biskuit dari tepung kedelai ternyata rendah karbohidrat dan cocok direkomendasikan untuk penderita diabetes. Kesimpulan ini didasarkan pada uji ilmiah, bahwa dari sekian jenis bahan makanan nabati, kedelai paling mudah dicerna dibandingkan dengan beras dan gandum.
Eksperimen ilmiah kedelai di Eropa lantas dikembangkan secara masif di Hindia Belanda. Di negeri jajahan, orang-orang Eropa awalnya enggan mengonsumsi kedelai karena derajatnya dianggap lebih rendah daripada bahan-bahan makanan Eropa, seperti terigu, mentega, keju, dan daging. Keengganan mereka juga didasarkan oleh sentimen kolonial yang menilai bahwa kedelai hanya dikonsumsi sebagai volksvoedsel (makanan rakyat) di negeri jajahan. Greshoff sendiri melaporkan semakin tingginya konsumsi kedelai di Pulau Jawa. Masyarakat di Jawa Tengah pada umumnya mengolah kedelai untuk dibuat tempe sebagai makanan pokok mereka.
Pada awal abad ke-20, penyelidikan ilmiah di balik kandungan gizi tempe terus berkembang pesat. Peneliti gizi, FW Donath, pada 1932 dalam artikelnya, De Voedingswaarde der sojaboon en enkele daaruit bereide specifiek Indische voedingsmiddelen (nilai gizi kedelai dan beberapa makanan khas pribumi yang secara khusus dibuat darinya) mengungkapkan hasil risetnya tentang tempe sebagai salah satu produk makanan kedelai populer di Hindia.
Menurut dia, tempe kaya dengan kandungan zat putih telur (albumin) dan diperlukan terutama bagi mereka yang menjalankan praktik vegetarian. Di samping menyingkap kandungan gizi kedelai, Donath juga mendukung upaya Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan sebagai agen penyokong pertumbuhan produksi kedelai diikuti kampanye peningkatan konsumsinya bagi masyarakat di Hindia.
Popularitas tempe
Popularitas tempe meningkat terus sepanjang dekade 1930-an hingga 1940-an ketika dunia tengah dilanda depresi ekonomi global. Pada masa itu, di Indonesia, suplai produk-produk protein hewani (daging, susu, dan mentega) melangka dan harganya melangit. WG Fisher van Noordt, seorang dokter, pada 1941 menulis sebuah artikel berjudul De Samenstelling van ons menu (susunan menu makan kita). Ia menyarankan agar para pembacanya terutama dari kalangan Belanda untuk mengonsumsi bahan nabati yang memiliki nilai nutrisi untuk menyubstitusi sumber protein hewani. Tempe dan olahan kedelai lainnya ia rekomendasikan sebagai pilihan pokok untuk diasup pada masa sulit.
Pada masa Perang Dunia II, manfaat tempe semakin terbukti nyata seperti dialami oleh orang-orang Eropa yang mengalami kondisi malnutrisi ketika mereka menjadi tawanan perang Jepang. Tempe dijadikan sebagai asupan penting untuk mengatasi kekurangan protein dan mampu mengurangi angka kematian di kalangan para tahanan perang.
Pasca-kemerdekaan, Pemerintah Indonesia memiliki program untuk memperbaiki kesejahteraan gizi rakyat. Pada dasawarsa 1950-an, ahli gizi Poorwo Soedarmo melalui Lembaga Makanan Rakyat gencar mengampanyekan semboyan ”Empat Sehat, Lima Sempurna”. Dalam semboyan ini terkandung anjuran untuk menyusun standar menu ideal hidangan Indonesia yang salah satu unsurnya mencakup tempe dan olahan kedelai lainnya.
Selepas masa perang, perhatian mancanegara terhadap tempe semakin besar. Amerika Serikat adalah negara yang terus mengembangkan dirinya sebagai produsen kedelai. Angka produksinya yang fantastis dari tahun ke tahun menjadikan kedelai sebagai salah satu bahan konsumsi pokok bagi warga Amerika Serikat. Sejak 1970-an, tempe menjadi salah satu produk olahan kedelai populer dan juga menjadi perkembangan penting bagi sektor kuliner di ”Negeri Paman Sam” itu.
Pada 1979, dua peneliti ahli kedelai, William Shurtleff dan Akiko Aoyagi, menerbitkan The Book of Tempeh lalu diikuti Tempeh Production pada 1980. Kedua penulis buku ini menunjukkan fakta bahwa tempe telah dianggap sebagai super food di mancanegara. Perusahaan produksi tempe di Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda terus berkembang pesat sejak dekade 1970-an. Uniknya, kebanyakan dari pelaku bisnis ini dijalankan justru bukan oleh orang Indonesia.
Tidak berlebihan Onghokham mengungkapkan tempe adalah bukti ”sumbangan Jawa untuk dunia”. Nyatanya memang makanan ini kini telah diterima oleh lidah masyarakat di mancanegara. Namun, apa yang diungkapkan sang sejarawan menjadi ironi ketika kini Amerika Serikat telah berhasil memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negerinya sendiri, justru sebagian besar kedelai yang dipakai untuk bahan baku produksi tempe di Indonesia adalah impor dari Negeri Paman Sam.
Dari menilik jejak masa lalunya, perlu dimafhumi bahwa pamor tempe sekarang ini sebagai super food tidak bisa dilepaskan dari campur tangan agen-agen kolonial. Melalui riset ilmiah dan strategi pangan yang sinergis, mereka memikirkan bagaimana martabat tempe bisa naik jika ditopang melalui keberlanjutan produksi kedelai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Tampaknya warisan ini yang tidak berlanjut setelah masa kemerdekaan. Di Indonesia, dari tahun ke tahun alih fungsi lahan pangan terus menyusutkan produksi kedelai dalam negeri.
Hal yang diwariskan justru stigma lama kolonialisme bahwa tempe adalah makanan rakyat jelata. Tidak heran ketika tahun 1980-an industri makanan instan dan cepat saji berkembang di Indonesia, manfaat gizi tempe yang digadang-gadang pada masa lalu cenderung meredup. Ketika negara-negara maju memuliakan tempe, di Indonesia sebagai negeri di mana makanan ini bermula, martabat tempe terkesan direndahkan mengingat semakin rendahnya pengetahuan gizi masyarakat.
Mungkin kita selaku ”bangsa tempe” tidak cukup jika hanya mengglorifikasi tempe sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia tanpa mengikuti pakem kriteria city of gastronomy yang ditetapkan oleh UNESCO melalui program Creative Cities Network-nya. Setidaknya tiga dari delapan kriteria berikut patut dipikirkan secara sinergis, yaitu tradisi gastronomi mengakar dan berkembang dengan baik; bahan-bahan baku lokal tetap digunakan dalam mengolah kuliner tradisional; serta sosialisasi pengetahuan gizi di lembaga-lembaga pendidikan disertai dengan upaya pemeliharaan biodiversitas pangan yang dimuat dalam kurikulum pendidikan.
Dalam konteks gastronomi, menghidupkan kembali kejayaan Indonesia sebagai produsen kedelai merupakan hal yang perlu dikedepankan untuk mengangkat martabat tempe. Jangan menjadi ironi, tempe sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia justru dihasilkan dari kedelai impor.
Catatan: Di-copy paste oleh redaksi Clakclik.com dari kompas.id (14/6/2021) untuk kepentingan edukasi publik
https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/13/martabat-tempe-dan-ironi-kedelai/