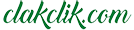Menikah, memiliki keturunan, dan membangun mahligai rumah tangga bahagia menjadi impian sejumlah insan di dunia ini. Namun, perkawinan dengan hubungan yang ”beracun” bisa menyakiti seseorang dan melanggengkan kekerasan.
Perkawinan sejatinya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
Namun bagi sejumlah perempuan (ada juga laki-laki), yang sebelumnya melewati masa pacaran dalam hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang ditandai dengan perilaku-perilaku toksik atau beracun (toxic relationship), perkawinan dengan keluarga yang bahagia dan kekal hanyalah slogan semata.
Jika hubungan beracun sewaktu berpacaran tidak dibereskan (dihentikan), maka perkawinan justru akan menjadi babak lanjutan dari hubungan beracun bagi salah satu pasangan.
Berbagai perlakuan buruk yang dialami semasa berpacaran bisa berlanjut dan mewujud dalam berbagai bentuk kekerasan, fisik, psikis, ekonomi, termasuk kekerasan seksual. Persoalan-persoalan seperti ini banyak menyandera, terutama kaum perempuan.
Ketika sudah masuk dalam jenjang perkawinan, hubungan beracun akan semakin menjerat perempuan, bahkan menyandera perempuan sehingga terjebak dalam lingkaran kekerasan yang terus berulang.
“Dalam konteks berpacaran dan belum tinggal serumah, intensitas kekerasan belum terlalu tinggi. Namun, ketika sudah menikah, menjadi suami istri dan tinggal serumah, disitulah intensitas kekerasan menjadi sangat mungkin meningkat,” ujar R Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan kepada Kompas, Senin (17/5/2021).
Valentina yang menulis buku “Cinta Itu Bukan Luka: Rahasia Terbebas dari Toxic Relationship” mengungkapkan perempuan sangat mungkin terjebak dalam perkawinan yang beracun dan menjadi korban, karena cara pandang masyarakat dipengaruhi budaya patriarki. Masih ada pandangan di masyarakat saat perempuan menikah dia menjadi properti (milik) suaminya, yang dapat diperlakukan seenaknya oleh pemiliknya.
Maka, ketika status hubungan berpacaran berpindah dalam status perkawinan, situasi perempuan akan semakin sulit, karena masyarakat memandang urusan rumah tangga adalah urusan privat dan orang lain tidak boleh ikut campur. “Ketika hubungan beracun terjadi dalam pacaran biasanya masyarakat masih mau intervensi, karena melihat pasangan tersebut belum menikah,” papar Valentina.
Hubungan yang tidak sehat atau beracun, sebenarnya disadari oleh sejumlah perempuan semenjak masa berpacaran. Bahkan ketika banyak orang berpikir bahwa hubungan beracun seharusnya ditinggalkan begitu pasangan melakukan kekerasan fisik atau verbal, bagi sejumlah perempuan langkah tersebut tidak mudah dilakukan.
Sebaliknya, sejumlah perempuan terpaksa meneruskan hubungan beracun tersebut ke jenjang perkawinan dengan berbagai alasan, meskipun harus menghadapi berbagai risiko yang buruk.
Misalnya, perempuan seringkali sulit memutus sebuah hubungan karena cenderung takut berpisah dan memilih menikah, meskipun pasangannya memiliki perilaku toksik. Sejumlah perempuan terikat dengan pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak baik jika berganti-ganti pacar.
Tidak hanya itu, ketika hubungan pacaran sudah berlangsung lama, apalagi jika hubungan sudah jauh sampai ke hubungan seksual, sejumlah perempuan yang berusia paruh baya cenderung memilih melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.
Faktor-faktor seperti itu sering membuat perempuan melanjutkan hubungan beracun ke arah perkawinan meskipun dia menyadari sebenarnya hal itu akan menjerat dia semakin terjebak pada siklus kekerasan.
Padahal saat perkawinan terjadi, apalagi ketika memiliki anak, maka perempuan akan semakin sulit keluar dari lingkaran hubungan beracun yang bisa jadi akan membawa petaka dalam hidupnya. Siklus kekerasan yang dialami perempuan akan terus berlanjut, karena atas nama melindungi anak, sejumlah perempuan meskipun mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, dan seksual di dalam rumah tangga, akan tetap memilih bertahan.
Risikonya tentu saja besar. Kekerasan yang sebelumnya ketika pada masa pacaran hanya sekali dua kali terjadi, ketika sudah dalam status perkawinan yang disahkan secara hukum dan tinggal bersama sebagai pasangan suami istri, bisa jadi insiden kekerasan akan meningkat. Risikonya, bisa berujung pada depresi berat bahkan sampai kehilangan nyawa.
Untuk menghindari hubungan beracun dalam perkawinan, yang bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selain membangun komitmen bersama antara pasangan yang akan menikah, sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan yakni melalui konseling atau kursus pra-nikah. Sejumlah agama telah menerapkan hal tersebut. Harapannya, agar pasangan yang akan menikah terhindar dari hubungan-hubungan yang tidak sehat, termasuk KDRT.
Sebab sejatinya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang berdasarkan penghormatan terhadap hak akan kebebasan dan martabat yang setara, saling menghormati, memberi dukungan dan memelihara satu sama lain.
Hubungan sehat memiliki ciri-ciri antara lain rasa kasih sayang, rasa aman, kebebasan dalam berpikir dan merasa, saling peduli, dan menyayangi, serta menghormati perbedaan pendapat atau pandangan yang ada. Bahkan, hubungan sehat mensyaratkan adanya komunikasi yang berkualitas. Kalau yang satu bicara, yang lain mendengarkan. Demikian sebaliknya.
Transformasi maskulinitas beracun
Nur Hasyim, pendiri Aliansi Laki-Laki Baru mengungkapkan, hubungan beracun sebenarnya juga terkait erat dengan toxic masculinity (maskulinitas beracun). Karena itu penting untuk mengenali pasangan laki-laki yang memiliki maskulinitas beracun.
Laki-laki yang memiliki maskulinitas beracun, biasanya memiliki keyakinan, sikap, praktik dan norma maskulinitas tradisional dan sempit yang membentuk kehidupan laki-laki, selalu merujuk pada kekuatan/superioritas, dominasi, agresivitas/kekerasan, petualangan, dan penaklukan.
Indikasi tersebut bisa terlihat dari cara pandangnya terhadap peran jender yang kaku, kepemimpinan itu ditentukan oleh jenis kelamin bukan talenta, menunjukkan kekuatan, aktif, dan agresif.
Selain itu, ada pandangan bahwa laki-laki harus menekan emosinya (sedih, takut, khawatir), pantang mencari pertolongan, merasa memiliki hak atas layanan seksual dari perempuan, mengontrol dan menguasai orang lain, laki-laki yang lebih lemah atau kelompok marginal, serta menggunakan kekekerasan atau ancaman kekerasan dalam menyelesaikan konflik. “Ada tiga tanda utama maskulinitas beracun yakni kekuasaan, kontrol, dan kekerasan,” ujarnya.
Untuk mengatasi maskulinitas beracun ini perlu ada transformasi, yakni dimulai dengan membuka ruang perbincangan tentang laki-laki dan maskulinitas, merefleksikan konsekuensi negatif dari maskulinitas beracun, mempromosikan konsep menjadi laki-laki manusiawi, hingga menjadi sekutu gerakan feminisme dalam aksi transformasi sistem sosial yang patriarki dan seksis sebagai akar maskulinitas beracun.
Bukan hanya itu, perlu didorong proses transformasi personal dan relasi yang sehat, dalam berbagai perilaku seperti tidak mentoleransi perilaku mengontrol, agresif, dan kekerasan, peduli kepada kepentingan dan aspirasi pasangan. Dengan begitu, menurut Nur Hasyim, mencintai seharusnya dimaknai sebagai membebaskan dan bukan memiliki atau menguasai.
Note: di-copy paste dari kompas.id (18/5/2021) untuk kepentingan edukasi publik.